Bab 4: The Divine Reality — Self-Evident
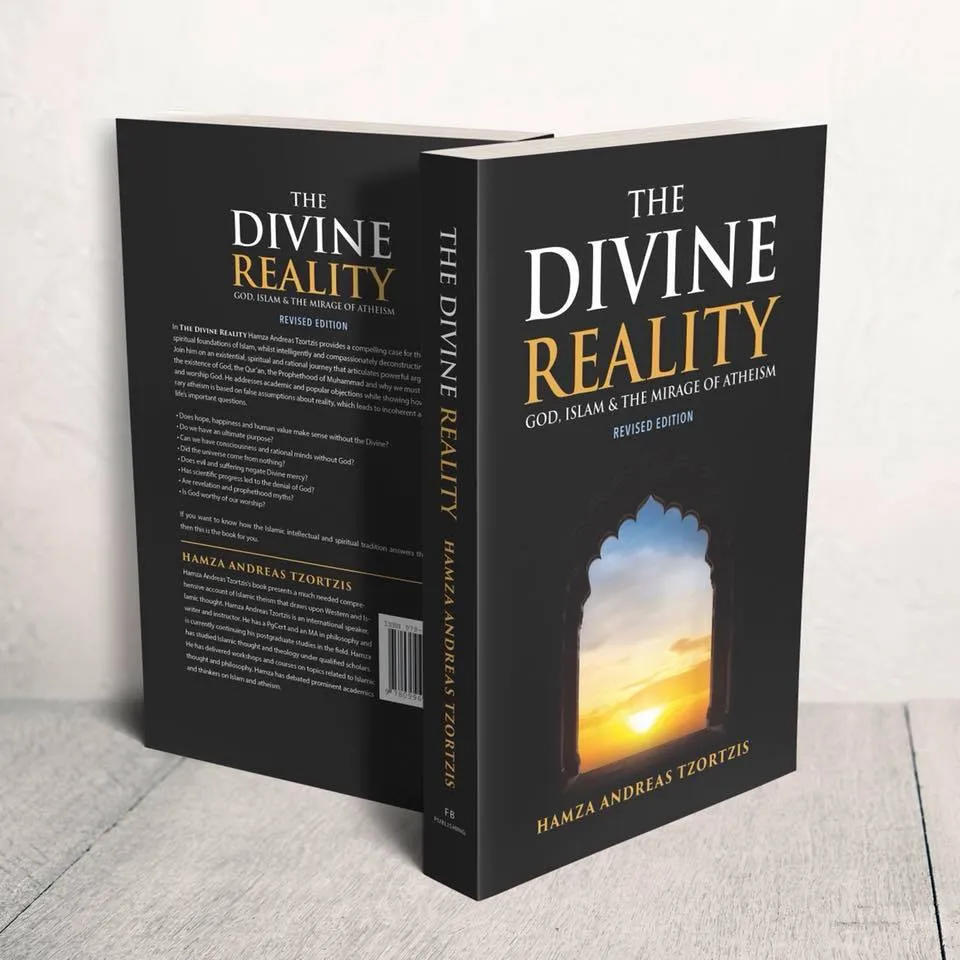
Suatu hari kamu dapat panggilan telfon dari sahabat lamamu. Dia minta ketemuan makan siang, ada urusan penting katanya. Tapi bukan untuk prospek MLM. Yasudah, karena ia sahabat lamamu kamu setuju untuk makan siang bersama. Pas ketemu, topik yang dia bicarakan malah membuat dahimu mengernyit: “Lo tau gak, masa lalu itu gak nyata. Yang lo lakaukan tadi, kemarin, seminggu yang lalu, dll itu gak nyata, cuma ilusi!“. Sebagai orang yang rasional, kamu pasti gak setuju. Dan, alih-alih kamu yang membuktikan masa lalu itu benar adanya, di sini kamu yang bertanya balik, “lo punya bukti gak yang mendukung pernyataan lo barusan?”
Karena akan aneh jadinya jika kita yang harus membuktikan masa lalu itu nyata. Kenapa? Karena masa lalu itu adalah sesuatu yang kebenarannya tidak perlu dibuktikan lagi (self-evident truth). Jika ada seseorang yang menentang ide tersebut, maka merekalah yang harus datang membawakan bukti, bukan kita.
Sama seperti seorang ateis yang mengklaim, “eh Tuhan itu gak nyata lho”. Kita tak perlu repot-repot menjawab dengan berbagai macam argumen, kitalah yang seharusnya bertanya balik Apakah ada alasan untuk menolak keberadaan Tuhan? karena posisi teisme itu posisi yang natural, the default position, bukan ateisme.
Self-evident Truths
Banyak hal di sekitar kita yang kebenerannya tak perlu dibuktikan lagi. Seperti:
- Realita masa lalu
- Validitas nalar kita
- Adanya pikiran (mind) lain
- Hukum sebab-akibat
- Keseragaman alam
Kenapa? Karena mereka memiliki karakteristik sebagai berikut:
- Universal. Tidak spesifik di kultur atau negara tertentu. Bukan berarti semua orang harus menerimanya, namun self-evident truth tidak lahir dari kondisi sosial tertentu.
- Tak diajarkan. Bukan hasil dari knowledge transfer.
- Natural. Terbentuk secara natural di dalam diri manusia. Seperti tertawa bila senang atau menangis kala sedih. Alami.
- Intuitif. Penjelasan yang paling sederhana dan komperhensif terhadap realita kita.
Masa lalu sebagai self-evident truth
Nah sekarang kita coba terapkan karekteristik di atas ke ‘masa lalu’. Apakah masa lalu itu universal? Ya pasti. Kemanapun kita pergi, hampir semua orang—bahkan mungkin semuanya—percaya bahwa masa lalu itu nyata, bahwa masa lalu adalah ‘saat ini’ yang telah terjadi. Apakah ia perlu diajarkan? Tidak perlu, karena tak ada seorang pun di dunia ini yang harus diajarkan oleh orangtuanya bahwa masa lalu itu nyata. Kenyataan ini ia dapatkan langsung dari pengalamannya sendiri. Realita masa lalu juga natural. Seseorang dengan akal sehat pasti setuju bahwasanya masa lalu adalah kumpulan hal-hal yang telah terjadi. Dan terakhir, ia juga intuitif karena sangat mudah sekali untuk percaya bahwa masa lalu itu nyata, tidak perlu penjelasan khusus. To believe otherwise raises more problems than it solves.
Tuhan sebagai self-evident truth
Universal
Kepercayaan pada Tuhan itu tak mengenal batas budaya dan negara. Di hampir segala penjuru dunia, banyak orang yang percaya pada konsep Tuhan atau entitas supernatural, walaupun konsep Tuhannya bermacam-macam. Ini berarti konsep Tuhan itu universal. Lagi, universal tidak berarti bahwa semua orang harus memercayainya, konsensus lintas budaya saja sudah cukup menjadi bukti bahwa belief kepada Tuhan itu tidak lahir dari kondisi sosial tertentu.
Kenyataannya, masih lebih banyak orang yang percaya Tuhan dibanding yang tidak. Dan ini sudah berlangsung selama ribuan tahun dari awal sejarah manusia.
Tak diajarkan
Percaya akan keberadaan Tuhan juga gak perlu diajarkan. Maka gak heran kalau banyak sosiolog dan antropolog berargumen kalaupun seorang anak kecil terdampar di sebuah pulau sendirian mereka akan tetap berkesimpulan pulau tersebut pastilah tidak muncul dengan sendirinya, ada seseorang yang menciptakannya. Nanti akan kita bahas ini lebih dalam di bawah dengan berbagai macam bukti penelitian.
Natural
Secara natural, kita menolak gagasaan adanya gedung tanpa seorang arsitek atau lukisan tanpa si pelukis, akan dianggap aneh kalau bilang demikian. Nah ini kan gak ada bedanya dengan alam semesta, ia tak mungkin muncul dengan sendirinya. Ibn Taymiyya menjelaskan bahwa afirmasi akan si Pencipta sudah tertanam di tiap-tiap hati manusia. Al-Raghib al-Asfahani, seorang ulama abad 12 juga menegaskan hal yang sama. Pun dari penelitian di berbagai macam bidang: kita sudah ditakdirkan untuk melihat dunia ini sebagai sesuatu yang memang diciptakan dan dirancang.
Intuitif
Tidak semua intuisi itu benar. Namun diperlukan bukti yang kuat agar seseorang bisa berubah pikiran dari intuisi awalnya. Misal, ketika kita di taman dan melihat barisan bunga-bunga bertuliskan ‘I love you’ secara intuitif kita menyimpulkan pasti ada seseorang yang mengerjakannya. Gak perlu mikir lagi. Simple. Jelas. Namun butuh usaha dan bukti yang sangat kuat untuk bisa meyakinkan orang-orang ini tu gara-gara angin tau! 🤪
Pun ketika sesorang melihat desain dan keteraturan di alam semesta ini, secara intuitif pastilah ada Penciptanya (Bab 8). Untuk membuatnya berpaling dari intuisi tersebut, diperlukan bukti yang valid untuk membenarkan pandangan sebaliknya (pandangan yang kontra-intuitif).
Bukti psikologis dan sosiologis
Seorang akademisi Olivera Petrovich dari Oxford melakukan penelitian tentang asal muasal objek natural seperti gunung, binatang, dan tanaman. Hasil yang ia temukan adalah anak-anak TK (pre-schoolers) memiliki tendensi tujuh kali lebih besar untuk berkesimpulan bahwa Tuhanlah yang menciptakannya dan bukan manusia. Partisipannya anak berumur 4 sampai 7 tahun di Inggris dan Jepang. Terlepas dari latarbelakang mereka, kebanyakan mereka menjawab Tuhanlah yang menciptakan dan tidak ada jawaban dengan nada agnostik seperti “gak ada yang tahu”. Petrovich menyebut penenumannya ini absolutely extroardinary karena agama Shinto di Jepang tidak memiliki gagasan Tuhan sebagai pencipta. Lalu bagaimana anak-anak Jepang ini bisa menjawab “Tuhan” sementara agama dan budayanya sendiri tidak mengajarkan demikian?
Mereka juga diminta untuk menjelaskan seperti apa sih Tuhan itu. Kita mungkin berekspektasi mereka akan menjelaskannya sesuai latarbelakang dan budaya mereka, namun ternyata tidak demikian. Kebanyakan menganggap Tuhan sebagai entitas tak bertubuh, seperti gas atau air. Petrovich menjelaskan bahwa konsep “Tuhan sebagai manusia” (seperti konsep trinitas) itu didapat dari pelajaran agama, namun tak ada anak yang secara natural menganggap Tuhan sebagai manusia dengan badan/tubuh.
Ia juga berkesimpulan bahwa ateisme itu ide yang harus dipelajari, sedangkan Tuhan adalah konsep yang natural. Lebih lengkapnya dijelaskan di bukunya yang berjudul Natural-Theological Understanding from Childhood to Adulthood.
Seorang psikolog dan profesor dari Yale University, Paul Bloom juga menegaskan demikian: bahwa penemuan-penemuan kontemporer di bidang psikologi kognitif mengindikasikan bahwa kepercayaan terhadap seorang desainer itu natural pada anak-anak.
Di artikelnya Are Children ‘Intuitive Theists’? Profesor Deborah Kelemen dari Boston University merangkum poin-poin yang ia temukan di penelitian-penelitian yang berfokus pada realita bahwa anak-anak melihat adanya purpose dan intention pada objek-objek natural,
A review of recent cognitive developmental research reveals that by around 5 years of age, children understand natural obejcts as not humanly caused, can reason about non-natural agents’ mental states, and demonstrate the capacity to view objects in terms of design. Finally, evidence from 6- to 10-year-olds suggests that children’s assignments of purpose to nature relate to their ideas concerning intentional nonhuman causation. Together, these research findings suggest that children’s explanatory approach may be accurately described as intuitive theism.
Ada juga penelitian yang dilakukan oleh Elisa Järnefelt, Caitlin Canfield and Deborah Kelemen, berjudul The dividend mind of a disbeliever: Intuitive belifes about nature as purposefully created among different groups of non-religious adults berkesimpulan bahwa orang dewasa pun juga memiliki kecenderungan melihat alam ini sebagai sesuatu yang didesain. Menariknya penelitian ini melibatkan orang-orang ateis juga: 352 orang dari Amerika utara (campur antara teis dan ateis), 142 dari Amerika Utara namun direkrut via organisasi/asosiasi non-relijius, dan 151 ateis dari Finlandia.
… non-religous participants in Nordic Finland where theistic cultural discourse is not present in the way it is in the US, default to vieweing both living and non-living natural phenomena as purposefully made by a non-human being when their processing is restricted.
Profesor Justin Barrett dari University of Oxford di bukunya Born believers: the science of children’s religious belief melihat kelakuan anak-anak dan berkesimpulan bahwa anak-anak ini terlahir dengan kepercayaan yang ia sebut “natural religion”. Ia juga menjelaskan bahwa konsep Tuhan terhadap anak-anak itu seperti mainan bentuk: otak kita sudah siap menerima “bentuk” (konsep) Tuhan.

… This tendency to see function and purpose, plus understanding purpose and order come from minded beings, makes children likely to see natural phenomena as intentionally created. Who is the Creator? Children know people are not good candidates. It must have been a god…
Untuk teman-teman yang penasaran bagaimana ia melakukan penelitiannya, bisa simak detail-nya di video berikut:
“Ah tapi kan anak-anak belum bisa membedakan mana imajinasi mana realita?” Betul, anak-anak mungkin belum bisa membedakannya, namun pernyataan ini pun secara metafisik bersifat netral. Artinya sesorang tidak bisa langsung saja berkesimpulan bahwa ateisme itu posisi yang benar, karena kesimpulan ini sendiri berdiri di atas asumsi bahwa ateisme itu benar dan teisme itu hanya fiksi belaka. Fakta ini pun juga tidak serta-merta membuat penemuan-penemuan di atas invalid. Harus ditekankan lagi bahwasanya penelitian-penelitian yang disebutkan di atas itu bersifat lintas kultur, yang berarti terlepas dari latarbelakang keagamaan si partisipan, mereka memiliki kecenderungan untuk berpikir layaknya seorang teis.
”Kebenaran Ateisme juga tak perlu dibuktikan lagi”
Beberapa ateis berargumen bahwa ateisme juga bisa jadi posisi default. Namun hal yang perlu disadari adalah: menolak gagasan adanya Sang Pencipta bukanlah penjelasan yang paling sederhana dan komperhensif. Sederhana sih mungkin aja, tapi tentu tidak komperhensif. Ia harus bisa menjelaskan bagaimana alam semesta yang kontingen ini (bergantung pada sesuatu yang lain, tidak independen. Dibahas di Bab 6) bisa tiba-tiba muncul dari ketiadaan (Bab 5). Bisa saja mereka menjawab persoalan asal muasal alam semesta ini dengan model lain, namun lagi, ia tidak self-evident, harus dipelajari, bukan default position.
Bawaan lahir: Fitrah
Tuhan sebagai self-evident truth sejalan dengan konsep Fitrah dalam Islam. Fitrah dapat diartikan sebagai kondisi alami yang ditanamkan oleh Tuhan di dalam hati manusia sejak lahir (innate disposition). “Bawaannya udah begitu dari sononya.”
Saya coba beri cotoh: balita. Semua yang pernah ngobrol sama balita pasti tau mereka ini hobi nanya-nanya. Kenapa ada hujan? Karena air turun dari awan. Kenapa awan bisa terbentuk? Oh karena ada matahari yang membuat air menguap. Kenapa air menguap? Teruuus aja nanya. Sampe capek. Nah ini bisa jadi bukti bahwa anak-anak memang punya intuisi akan konsep causation (sebab-akibat). Secara alami, kita memang terlahir untuk mencari tahu penyebab utama (ultimate causal ends) dari semua fenomena ini. Kita sudah dirancang untuk menemukan Tuhan sebagai jawaban akhir.
Kemampuan untuk mengenali dan menyembah-Nya juga sudah built-in di dalam Fitrah. Al-Qur’an memberi perumpamaan dengan seseorang yang berada di kapal yang terombang-ambing di lautan. “There are no atheists on a sinking ship”. Saat dihadapkan dengan situasi yang amat sulit, kita sebagai manusia secara natural akan mencari ‘kekuatan’ yang lebih tinggi ketika tak ada sesuatu lagi yang dapat dijadikan harapan.
Apabila orang-orang yang membangkang itu masuk dan menaiki kapal, kemudian mereka diombang-ambingkan oleh air laut dan ombak yang menggunung seakan-akan menaungi mereka sehingga mereka mengira bahwa mereka pasti akan tenggelam, mereka segera bergantung dan berlindung kepada Allah dan berdoa kepada-Nya dengan ikhlas dan tunduk untuk menolong mereka. Lalu apabila Allah telah menyelamatkan mereka sampai ke daratan, sedikit sekali dari mereka yang mengingat janjinya dan berjalan pada jalan yang lurus dalam setiap perbuatannya. Bahkan kebanyakan mereka lupa akan karunia Allah dan tetap membangkang. Sesungguhnya tidak ada yang mengingkari karunia dan kebaikan Tuhannya, kecuali orang yang sangat ingkar dan berlebih-lebihan dalam kekufurannya - QS 31:32
Ibarat sepeda motor yang baru keluar dari pabrik, Fitrah ini juga tak bisa luput dari ‘modifikasi’. Sejalan dengan hadits Nabi, “setiap anak terlahir dengan fitrah. Lalu orang tuanya yang membuatnya Yahudi, Kristiani, atau Majusi”. Kalau sudah termodifikasi, Fitrah dapat di-reset melalui introspeksi, refleksi, dan tadabbur.
… Demikianlah Kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan (Kami) kepada orang-orang berfikir - QS 10:24
Ah, tapi apa bisa dibuktikan dan sejalan dengan sains? Kita kan gak bisa tiba-tiba berargumen bahwa semua ini pasti karena Fitrah, hanya karena belum ditemukannya jawaban atas fenomena ini. Jawaban singkatnya: banyak hal yang gak bisa dijawab oleh sains, seperti asal muasal kecerdasan, rasionalitas, dan consciousness. Begitupun dengan Fitrah. Kita bisa mencari jawabannya melalui pendekatan lain, seperti melalui argumen yang rasional dan logis—seperti premis berikut:
“Segala sesuatu yang kita ketahui dan rasakan di kehidupan ini terbatas dan terbentuk dari lingkungan dimana kita berada.” Jika kita tinggal di dunia yang naturalistis ini dimana segalanya terbatas dan bersifat materialis, maka seharusnya pengertian kita pun terbatas pada fenomena-fenomena naturalistis saja. Kita tidak bisa membayangkan sebuah konsep yang tidak natural, tidak materialis, dan di luar dunia ini. Seperti seekor ikan yang berenang di dalam aquarium seumur hidupnya, ia tak akan pernah tau fakta bahwa ternyata ia berada di ruang tamu seseorang. Apa tuh ruang tamu? Atau seseorang yang gak pernah makan apel diminta untuk membayangkan rasa apel. Gak bisa! Kita pun seharusnya tidak akan pernah tahu, paham, dan percaya terhadap sesuatu yang supranatural (di luar dunia ini). Apalagi kalau kita ini memang produk evolusi yang berlangsung selama jutaan tahun, seharusnya apa-apa yang bisa kita bayangkan terbatas pada fenomena dunia yang naturalistis saja. Gak ada yang namanya supranatural. Tapi lucunya studi-studi di atas membuktikan hal yang sebaliknya; bahwasanya kita memang terlahir dengan kemampuan alami untuk mengenal Tuhan yang sifatnya supranatural, tak terbatas, dan melampaui fenomena-fenomena naturalistis. Berdasarkan premis di atas, bisa disimpulkan bahwa Fitrah secara logis tak dapat muncul dari dunia yang naturalistis dan materialistis ini. Sementara sains hanya bisa menjelaskan hal-hal yang sifatnya natural dan materialis.
Sebagai penutup, seorang ulama Wesam Charkawi menjelaskan bahwa keberadaan Tuhan ini sejalan dengan Fitrah kita:
Indeed, the first sense in the depth of a person if he contemplates within himself and in the world around him is the sense of a higher power that reigns over the world with the command to dispose over life and death, creation and annihilation, motion and stillness … In addition, we feel in ourselves the presence of compassion, love, hate, encouragement and dislike, though what is the proof that it exists, even while it flutters within us? Is one able to bring forth evidence more than that which he feels and senses, and yet it is real without doubt? One feels excitement and senses pain, yet is one unable to establish evidence to prove it exists with more than what he feels? Without doubt, this is the natural way [fitrah] or instinct on which mankind has been created … it is a natural truth that corresponds to the world.
Tambahan, berikut beberapa video yang membantu saya menulis artikel ini:
… [Bersambung ke Bab 5]