Bab 3: The Divine Reality — Musuh Akal
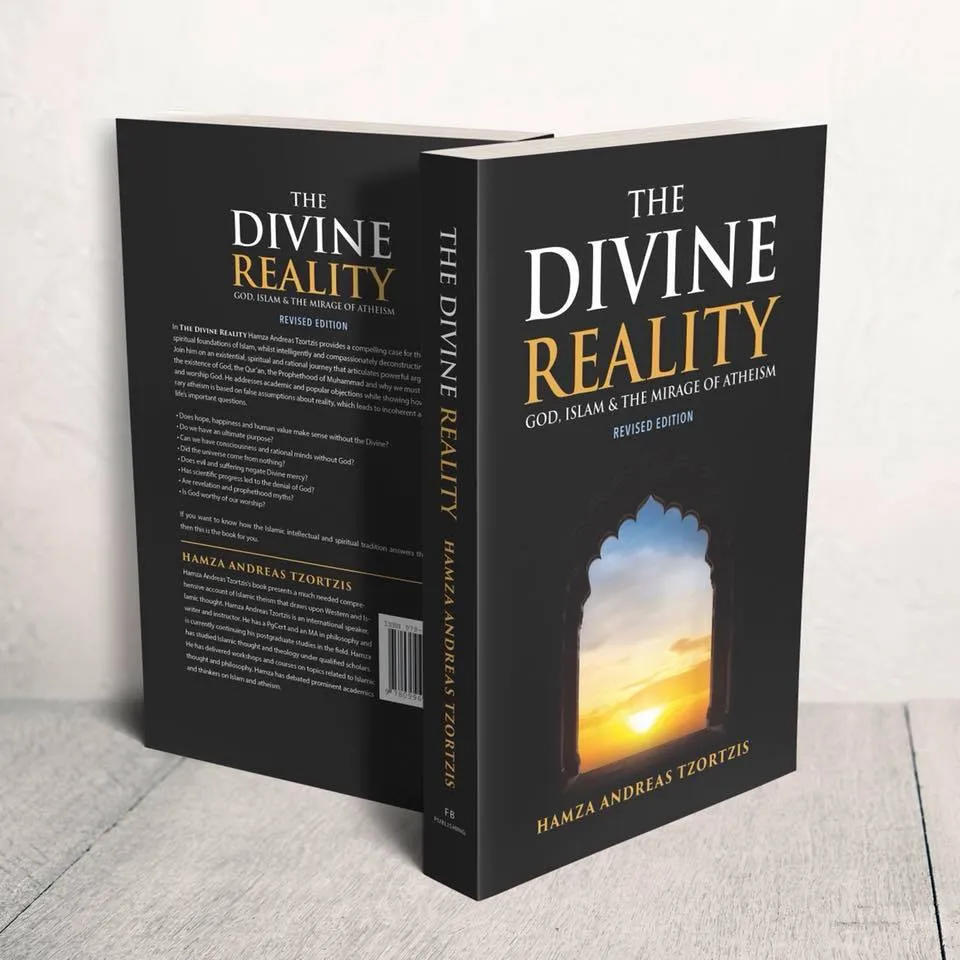
Anggap saja kamu seorang supir taxi yang baru dapat order di bandara. Kamu bertukar salam dengan si penumpang, berbasa-basi, lalu mengantarnya sampai ke tujuannya di pelosok desa.
Sekarang coba ulangi cerita barusan, kali ini kamu berkendara dengan mata tertutup. Apa kamu masih bisa mengantarnya sampai tujuan? Jawabannya jelas enggak. Bagaimana kalau kamu justru bilang ke penumpang bahwa kamu tetap bisa mengantarnya sampai ke tujuan? Gile lu, katanya.
Nah paham ateisme ini 11-12 dengan supir yang mengaku bisa berkendara dengan mata tertutup. Lho kenapa bisa begitu?
Sebelumnya, mari kita bahas kenapa analogi di atas cocok digunakan sebagai perbandingan antara Islam dengan ateisme. Baik orang Muslim atau ateis, keduanya mengaku punya kemampuan bernalar. Artinya kita bisa membuat dan membentuk pikiran yang rasional: kita bisa “melihat” jalan pikiran kita dan hinggap di suatu kesimpulan. Nalar kita mengambil premis (atau pernyataan) dan “mengantarkan” kita ke suatu tujuan (konklusi yang logis).
Nah karena banyak ateis yang berpandangan naturalis—dimana semua fenomena, termasuk proses bernalar kita ini, hanya bisa djelaskan dengan proses-proses fisik yang buta dan non-rasional (tidak memiliki kemauan sendiri, tak berakal, benda mati)—maka gak heran seorang ateis itu persis seperti supir taxi yang berkendara dengan mata tertutup. Dia tidak akan bisa mengantar penumpangnya sampai ke tujuan. Pun dengan proses-proses fisik yang buta ini, mereka tidak akan pernah bisa “mengantar” premis-premis di pikiran kita ke suatu kesimpulan yang logis.
Kemampuan kita bernalar simple-nya gak masuk di paham naturalisme, karena rasionalitas tidak bisa datang dari proses-proses fisik yang buta dan non-rasional. Untuk tetap beranggapan demikian sama halnya dengan bilang sesuatu bisa saja muncul dari ketiadaan (something can come from nothing).
Lalu mengapa pandangan Islam seperti supir taxi yang bisa melihat (gak pakai penutup mata)? Dalam Islam kemampuan kita berakal datang dari Dia yang Maha Melihat dan Maha Mengetahui. A thing cannot give rise to something if it does not contain it, or if it does not have the ability (or the potential) to give rise to it. Oleh karenanya, akal dan nalar kita hanya bisa muncul dari Sang Pencipta.
Apa itu Nalar?
Dalam konteks tulisan ini, nalar adalah sesuatu yang memungkinkan kita untuk menangkap kebenaran, menemukan, dan menyimpulkan sesuatu (infer, induce, dan deduce—saya gak tahu translasi yang tepat hehe). Ketika kita bernalar secara logis, kita memiliki kemampuan untuk mengaitkan premis dengan kesimpulan, bahkan ketika premis-premis yang tersedia terdengar asing di telinga kita. Contoh:
- Semua domba punya cicionggong.
- Shaun adalah seekor domba.
- Maka, Shaun punya cicionggong.
Kita tahu bahwa [3] pasti mengikuti premis [1] dan [2], meskipun kita belum tahu apa itu cicionggong. Namun tak ada yang bisa menjelaskan di dunia ini (secara fisikal maupun secara empiris) kenapa [3] berkaitan dengan [1] dan [2], kenapa kita bisa “melihat” benang merah antara kesimpulan dengan premis-premis sebelumnya. Namun tetap, otak kita punya kemampuan untuk bernalar dan dapat mengarahkan kita untuk sampai ke kesimpulan [3].
Sayangnya, “mengarahkan” ke suatu tujuan itu bukan atribut dari proses-proses fisik: karena mereka buta, non-rasional, tak berakal, tak bertujuan, dan tak memiliki kemauan maupun kapasitas untuk mengarahkan premis-premis tersebut ke suatu kesimpulan, yang merupakan ciri dari rasionalitas. Kita tak bisa mendapatkan insight dari sesuatu yang buta. Oleh karenanya, rationality cannot come from non-rational physical processes.
BTW, cicionggong itu gibberish anak balita saya 😅
Nalar sebagai Sebuah Asumsi dalam Sains
Manusia itu spesial: kita mampu membedakan mana yang benar mana yang salah, mana yang bagus dan mana yang kurang bagus. Kemampuan ini juga yang kita manfaatkan untuk melakukan eksperimen sains. Bahkan, kita harus yakin dengan kecakapan rasionalitas kita sebelum dapat melakukan eksperimen sains karena salah satu asumsi dasar dalam sains adalah kita (atau si saintis) memiliki kemampuan untuk bernalar. Tanpa adanya asumsi ini, kata “bukti” atau “fakta” gak akan pernah muncul di kamus.
Tapi bukan berarti sains tak memiliki penjelasan sama sekali terkait (mekanisme) kemampuan kita bernalar. Poinnya adalah sains hanya bisa berurusan dengan hal-hal yang bisa diobservasi; sedangkan logical relations antar premis itu mustahil untuk diobservasi. Menganggap sains dapat memberikan penjelasan yang utuh terhadap kemampuan kita bernalar sama saja seperti arguing in a circle, karena si saintis sendiri harus mengandalkan nalarnya untuk menjelaskan nalar itu sendiri. Ia harus yakin—bukan hanya yakin, malah harus bisa membuktikan—bahwa nalarnya bekerja dengan baik untuk bisa memberikan penjelasan tentang nalar yang saintifik. Sains juga punya batasan (dibahas di Bab 12).
Nalar Muncul Dari Evolusi (Darwinian)?
Menurut para naturalis, akal dan nalar kita telah berevolusi untuk jadi rasional, agar kita lebih tahu lingkungan di sekitar kita yang pada akhirnya memberikan kesempatan bertahan hidup lebih baik. Kedengarannya masuk akal! Tapi ternyata, Darwin sendiri meragukan ide ini di sebuah surat yang ia tulis pada tahun 1881: “But then with me the horrid doubt always arises whether the convictions of man’s mind, which has been developed from the mind of the lower animals, are of any value or at all trustworthy. Would anyone trust in the convictions of a monkey’s mind, if there are any convictions in such a mind?”
Namun mari tetap bahas mengapa argumen evolusi dapat melahirkan nalar adalah sesuatu yang absurd:
- Kemampuan kita membedakan kebenaran dengan kebohongan itu bukanlah syarat dalam bertahan hidup.
- Kemampuan bernalar (having mental insights) juga bukan merupakan syarat dalam meneruskan keturunan. Evolusi itu untuk bertahan hidup, bukan untuk berlogika ria.
- Rasa penasaran dan kemampuan kita dalam melakukan suatu penemuan—salah satu ciri akal yang rasional—sering kali bertentangan dengan kelangsungan hidup kita sendiri.
Apa benar sesuatu tetap bisa bertahan hidup walau dengan keyakinan yang salah (false belief) dan tidak rasional? Seorang profesor filsafat, Anthony O’Hear memberikan sebuah contoh yang membuktikan bahwa evolusi dapat melahirkan keyakinan yang salah namun justru malah membuatnya bertahan hidup: Seekor burung bisa saja menghindari tipe-tipe ulat yang beracun berdasarkan warnanya; namun ia juga akan menghindari ulat yang tak beracun dengan warna yang mirip-mirip. Ini kan false belief, karena tidak semua ulat dengan warna tersebut beracun. Tapi tentu saja kelangsungan hidup burung tersebut meningkat karena ia menghindari memakan tipe-tipe ulat tersebut, yang beracun maupun yang tidak. Begitupun dengan ulat-ulat yang tak beracun ini, mereka jadi bisa bertahan hidup lebih lama dan menjadi hasil sampingan (by-product) dari proses evolusi ini dengan mimikri atau dengan meniru warna ulat yang beracun.
… we have here an evolutionary explanation of falsehood, reinforcing the general point that there is no direct way of moving from evolutionary workings to truth.
Dari sini muncul pertanyaan: Haruskah kita percaya dengan akal pikiran kita? Karena tak ada korelasi antara kebenaran dengan kelangsungan hidup—dan dengan false belief-pun kita bisa bertahan hidup—maka bagaimana kita bisa percaya dengan kemampuan nalar kita sendiri jika ia bisa saja muncul dari proses evolusi yang didorong oleh false belief?
Rasa penasaran dan kemampuan kita untuk melakukan suatu penemuan juga bisa menjadi masalah dalam kelangsungan hidup. Kita tak perlu repot-repot belajar fisika atau matematika untuk berevolusi, untuk meneruskan keturunan, atau untuk bertahan hidup. Kecoa aja bisa hidup selama jutaan tahun, dan kita gak pernah lihat tuh mereka lagi ngopi-ngopi ala anak senja ngebahas eksistensi hidup dan implikasi dari paham ateisme.
Sementara kita, manusia, sering kali melakukan sesuatu yang tidak kondusif untuk kelangsungan hidupnya sendiri hanya untuk mencari kebahagiaan. Seperti mendaki gunung Everest yang berbahaya, atau main buggy jumpy, atau eksplorasi ke luar angkasa tanpa adanya jaminan si astronot akan selamat sekembalinya ke bumi.
Sudah jelas bahwasanya teori evolusi Darwin yang mengarah pada kelangsungan hidup, bukan pencarian kebenaran, tidak cukup untuk menjelaskan kehausan kita akan discovery.
Ilmuan biologis John Gray menyatakan, “If the human mind has evolved in obidience to the imperatives of survival, what reason is there for thinking that it can acquire knowledge of reality, when all that is required in order to reproduce the species is that its errors and illusions are not fatal? A purely naturalistic philosophy cannot account for the knowledge that we believe we possess.”
Penemu DNA Francis Crick berkata, “Our highly developed brains, after all, were not evolved under the pressure of discovering scientific truths, but only to enable us to be clever enough to survive and leave descendants.”
Ilmuan kognitif Steven Pinker pernah menulis, “Our brains were shaped for fitness, not for truth. Sometimes the truth is adaptive, but sometimes it is not.”
Sam Harris, seorang neurosaintis dan ateis yang blak-blakan, walaupun ia percaya bahwa sains pada akhirnya akan memberikan jawaban, mengaku bahwa, ”… our logical, mathematical, and physical intuitions have not been designed by natural selection to track the Truth.”
Sebuah Catatan tentang Evolutionary Reliabilism
Terlepas dari argumen di atas, banyak naturalis yang tetap meyakini bahwa di bawah situasi dan tekanan biologis tertentu, evolusi dapat memunculkan kemampuan-kemampuan kognitif yang dapat diandalkan untuk melahirkan true belief. Tentunya kemampuan-kemampuan kognitif ini harus fitness enhancing (kondusif untuk kelangsungan hidup dan reproduksi suatu organisme) dibanding kemampuan-kemampuan non-kognitif yang melahirkan false belief.
Namun kita tahu dari contoh burung sebelumnya yang menghindari tipe ulat dengan warna tertentu, memiliki kemampuan non-kognitif tidak menurunkan kesempatan bertahan hidupnya begitu saja. Seorang akademis James Sage berargumen,
For example, an organism may hide because it believes falsely that a predator is nearby. Evolutionarily, it pays to have cautious belief-forming processes that “over detect” dangerous predators, especially when false beliefs carry little cost.
Sementara itu, untuk melahirkan kemampuan kognitif yang dapat diandalkan untuk melahirkan true belief, dibutuhkan biaya biologis yang cukup mahal karena:
- Otak butuh oksigen, kalori, dan waktu untuk istirahat.
- Bernalar dengan detil butuh waktu dan konsentrasi.
- Mengakses memori dari pengalaman masa lalu membutuhkan tempat penyimpanan yang tak sedikit.
- Mengindentifikasi informasi-informasi yang relevan membutuhkan multi-level sorting subroutine (subrutin adalah kumpulan-kumpulan instruksi yang bakal sering dijalankan).
- Menata keinginan dan tujuan butuh pertimbangan dan pemikiran yang ekstensif.
- Memanfaatkan “detektor” atau suatu indra membutuhkan presisi dan ketajaman. Kesemua ini punya beban biaya biologis yang besar.
Nah karena untuk melahirkan kemampuan kognitif yang bisa diandalkan saja butuh biaya bilogis yang tidak sedikit hanya untuk bertahan hidup, seleksi alam pastilah memilih kemampuan yang non-kognitif karena biaya biologisnya jauh lebih sedikit.
Rasionalitas Muncul dari Kompleksitas
Sebagian orang bilang bahwa suatu properti baru bisa saja muncul dari proses fisik yang kompleks. Contoh yang sering dipaparkan adalah air. Air terbuat dari hidrogen dan oksigen yang merupakan gas, namun ketika digabungkan menjadi benda cair.
Namun contoh air ini tidak cocok dijadikan argumen karena bahasan bab ini bukan tentang bagaimana suatu benda fisik (air) dapat muncul dari benda fisik lainnya (hidrogen dan oksigen), namun bagaimana munculnya properti non-fisik (rasionalitas, kemampuan bernalar) bisa terjadi dari properti fisik (proses-proses fisik yang buta itu).
Pertanyaan lain yang harus ditanyakan ke mereka: Harus seberapa rumitkah suatu proses agar ia bisa melahirkan rasionalitas? Berapa jumlah molekul dan energi yang dibutuhkan?
Lalu jika ada orang yang bilang properti baru bisa saja muncul dari proses yang rumit tanpa menjelaskan bagaimananya, kan sama saja seperti seorang tukang yang bilang kita bisa bikin rumah dari batu bata. Padahal ada proses-proses lain yang harus dijelaskan seperti nyemen, bangun pondasi, dan lain-lain. Ngapain ada teori kalau begitu.
Lho Tapi Komputer Mikir, Ia Rasional
Jawaban singkatnya: kan komputer dibuat oleh manusia yang juga rasional. Balik ke prinsip awal, a thing cannot give rise to something if it does not contain it, or if it does not have the ability (or the potential) to give rise to it.
Willian Hasker menjelaskan,
Computers function as they do because they have been endowed with rational insight. A computer, in other words, is mereley an extension of the rationality of its designers and users; it is no more an independent source of rational insight than a television set is an independent source of news entertainment.
Tapi kalau dibahas lebih dalam, komputer sendiri sebenernya ‘tidak mengerti’ apa-apa. Dari luar saja terlihat seolah-olah mereka itu benda yang pintar dan rasional. Profesor John Searle memiliki analogi yang kira-kira begini:
“Misal kamu gak ngerti karakter Mandarin lalu kamu ditempatkan di suatu ruangan dengan beberapa kotak berisi karakter-karakter Mandarin. Kamu juga diberi buku instruksi bagaimana cara menyusun suatu karakter dari kotak-kotak tersebut. Lalu kamu diberi sesuatu yang orang-orang di luar ruangan menyebutnya ‘pertanyaan’ dan kamu diminta untuk mengolahnya berdasarkan buku instruksi tersebut. Hasil olahanmu ini orang-orang menyebutnya ‘jawaban’. Dan ketika kamu berhasil ‘menjawabnya’, mereka pikir kamu ini pintar dan mengerti karakter Mandarin. Padahal kamu hanya mengikuti instruksi dari buku tanpa mengerti arti karakter-karakter tersebut.”
Ini menunjukkan bahwa sintaks (karakter) dan semantik (makna/arti) adalah dua hal yang berbeda. Cara kerja komputer itu gak beda jauh dengan kamu yang ada di ruangan tadi, kalian hanya tahu sintaks tanpa tahu semantiknya.
Kalau ada tanah longsor di gunung eh tiba-tiba terbentuk tulisan ‘I love you’, kamu bakal dianggap gak sehat kalau menganggap gunung tersebut mengerti arti tulisan ‘I love you’. Inilah perbedaan antara manusia yang berakal dan bernalar dengan komputer yang hanya ‘mengerti’ sintaks.
Islam: Penjelasan Terbaik
Dari prinsip-prinsip yang sudah kita bahas bersama di atas, maka penjelasan yang paling sederhana dan masuk akal tentang bagaimana munculnya kemampuan nalar kita adalah bahwa ia datang dari Yang Maha Melihat, Maha Mengetahui, dan Maha Bijaksana, yaitu Sang Pencipta.
Jika pada awal terbentuknya alam semesta ini hanya ada proses dan materi fisik yang acak, buta, dan non-rasional, maka tak peduli seberapa rumitnya mereka tersusun, rasionalitas tak akan muncul darinya. Sebaliknya, jika pada awal terbentuknya alam semesta ini sudah ada satu Entitas yang nama dan atributnya disebut di paragraf sebelumnya, maka masuk akal bila di alam semesta ini terdapat makhluk hidup yang memiliki nalar dan rasionalitas.
”Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kebesaran) Kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidak cukupkah (bagi kamu) bahwa Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu?” — QS 41:53
“Tidakkah kamu memikirkannya (menggunakan akal dan nalarmu)?” — QS 11:51
“Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi orang yang berakal” — QS 3:190
Dari sini bisa kita simpulkan bawha Tuhan telah memberi kita akal yang rasional dan hasrat untuk melakukan penemuan, supaya kita gunakan nalar ini untuk memahami alam semesta beserta keindahannya, yang pada akhirnya menggiring kita untuk menyembah-Nya (Bab 15). Ia telah menanamkan sarana dan instrumen yang kita tunggangi untuk sains, namun ironisnya sebagian dari kita malah menggunakannya untuk menentang Penciptanya sendiri.
… [Bersambung ke Bab 4]