Bab 2: The Divine Reality — Hidup Tanpa Tuhan
May 14, 2021 20:19 · 2664 words · 13 minute read
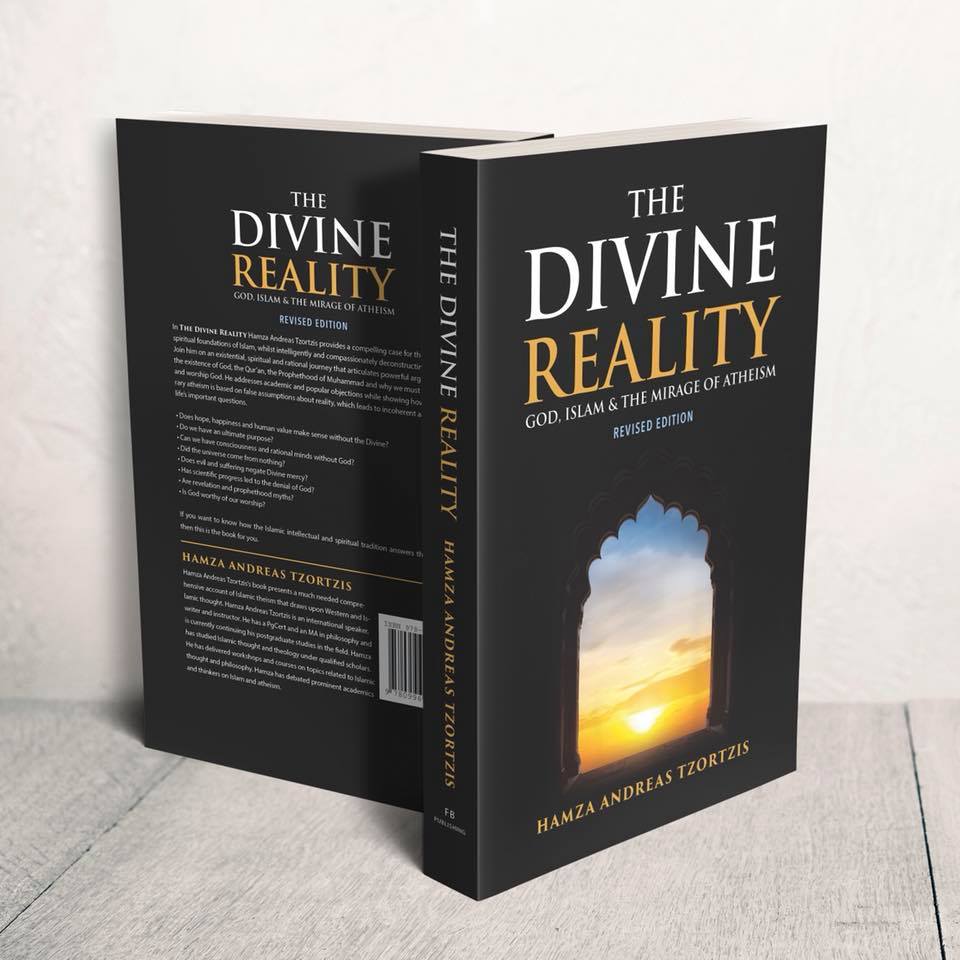
Hidup di bawah ateisme itu lucu. Penjelasan di bawah nanti mungkin gak bisa dijadikan bukti rasional untuk menunjukkan keberadaan Tuhan namun tetap menjadi landasan argumen-argumen yang ada di buku ini. Seperti yang sudah dibahas di Bab 1, kebanyakan ateis itu mengikuti paham naturalisme dimana segala sesuatu bisa dijelaskan dengan proses fisik (gak ada yang namanya supranatural). Ateisme + Naturalisme = Ambyar. Tidak ada Tuhan = tidak ada konsep pertanggungjawaban = tidak ada nilai, tujuan, dan harapan di dunia ini. Mari kita bahas.
Tidak Ada Harapan
Harapan dapat diartikan sebagai suatu perasaan atau ekspektasi akan terjadinya sesuatu. Kita semua pasti aja berharap yang baik-baik, mulai dari pekerjaan, pasangan, keberuntungan, dan lain sebagainya. Pada akhirnya kita semua ingin kebahagiaan yang abadi. Di sisi lain, kita juga ingin adanya suatu keadilan dimana yang salah dibuat benar (diadili) dan orang-orang yang berbuat demikian bertanggungjawab. Terlebih bagi kita yang hidupnya kurang beruntung: kita ingin kemudahan, kedamaian, juga kenyamanan. Ini sangat manusiawi. Kita ingin adanya cahaya di ujung lorong yang gelap.
Bandingkan dengan pandangan ateisme. Karena mereka tidak percaya dengan adanya “dunia di luar dunia kita” (konsep hari akhir), maka harapan untuk mendapatkan kesenangan itu hanya sia belaka. Bayangin aja kalo kamu dari lahir sudah hidup sengsara, menurut paham ateisme hidupmu ini sama seperti kalimat “mati aja lo”, no hope at all. Sedangkan dalam Islam, kesengsaraan dan ketidaknyamanan yang kita rasakan di dunia ini gak akan sia-sia. Allah tahu dan akan mengganjarnya (Bab 11).
“… Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir.” — QS 12:87
Karena mereka tidak percaya dengan konsep hari akhir, otomatis mereka juga tidak percaya dengan konsep pertanggungjawaban amal. Bayangkan seorang ibu Yahudi yang hidup pada tahun 1940-an (ketika Nazi berkuasa) yang menyaksikan suami dan anak-anaknya dieksekusi di depan matanya. Dan ia sedang menunggu gilirannya dieksekusi. Walaupun mereka pada akhirnya dikalahkan, tapi keadilan ini tidak ia dapatkan semasa hidupnya. Di bawah paham ateisme, ibu ini bukan apa-apa, hanya sekumpulan molekul dan atom tak bernyawa yang kebetulan disebut manusia. She didn’t deserve anything, let alone justice.
Sementara dalam Islam, semua hal yang kita lakukan ada balasannya dan akan dimintai pertanggungjawabannya. Perbuatan kejam para Nazi dulu juga akan diadili.
• يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ ٱلنَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا۟ أَعْمَـٰلَهُمْ • فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُۥ
“Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok, untuk diperlihatkan kepada mereka (balasan) semua amal perbuatannya • Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya • Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya.” — QS 99:4-6
Tidak Ada Nilai
Apa bedanya manusia sama martabak? Hehe, ini pertanyaan serius kok. Menurut ateis yang menganut pandangan naturalistik, keduanya gak ada bedanya: hanya berupa susunan materi yang konon terbentuk dari proses acak dan non-rasional (it just happens).
Kalau betul demikian, lalu apa manusia itu tetap punya “nilai”?
Misal nih, tak ambil palu terus tak pukul itu martabak sama kepalamu. Menurut mereka, serpihan martabak dan kepalamu ini sama aja, sama-sama terbuat dari materi tak bernyawa.
Jawaban yang biasa dilontarkan adalah: manusia itu makhluk hidup, punya nyawa, dan punya perasaan. Tapi balik lagi, menurut pandangan naturalistik, emosi manusia itu pada hakikatnya adalah hasil dari berbagai reaksi kimia yang terjadi di dalam otak, yang juga merupakan susunan-susunan materi saja. Rasa sedih, senang, sakit, nikmat, semuanya sama, tak lebih dari reaksi kimia semata.
Kita bisa saja bilang, manusia lebih berharga dibanding martabak karena struktur manusia itu lebih kompleks. Tapi ingat, lagi-lagi, menurut mereka tidak ada sesuatupun di dunia ini yang didesain dan diciptakan dengan suatu tujuan. Ini semua hanyalah susunan materi yang terbentuk dari proses acak, buta, dan non-rasional.
Dalam pandangan Islam, manusia dilahirkan dengan “bawaan” yang sama, yang nantinya dapat membantu mengenali harga diri kita sebagai manusia sekaligus mengenali nilai-nilai moral dan etika (Bab 9). Bawaan ini disebut fitrah (Bab 4).
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِىٓ ءَادَمَ وَحَمَلْنَـٰهُمْ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ وَرَزَقْنَـٰهُم مِّنَ ٱلطَّيِّبَـٰتِ وَفَضَّلْنَـٰهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا
“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna.” — QS 17:70
رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَـٰذَا بَـٰطِلًا سُبْحَـٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ …
“… Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia; Mahasuci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka.” — QS 3:191
Karena paham naturalisme ini menolak ide adanya segala bentuk keadilan Tuhan, ‘ganjaran’ yang diberikan ke seorang kriminal dan seorang pendamai itu sama saja: kematian. Kalau ‘ujung’ nasib seorang Hitler dan seorang Soekarno itu sama saja, lah terus dimana nilainya manusia? Ngapain capek-capek berbuat baik? Wong orang baik sama derajatnya dengan orang jahat. Sudah jelas kan, paham ini tidak memberikan value yang berarti kepada kita sebagai manusia.
Seyyed Hossein Nasr, seorang profesor studi Islam dari Universitas George Washington, memberikan testimoni yang menarik mengenai martabat dan hak asasi manusia,
Before speaking of human responsibilities or rights, one must answer the basic religious and philosophical question ‘What does it mean to be human?’ In today’s world everyone speaks of human rights and the sacred character of human live and many secularists even claim that they are true champions of human rights as against those who accept various religious worldviews. But strangely enough, often those same champions of humanity believe that human beings are nothing more than evolved apes who in turn evolved from lower life forms and ultimately from various compounds of molecules. If the human being is nothing but the result of ‘blind forces’ acting upon the original cosmic soup of molecules, then is not the very statement of the sacredness of human life intellectually meaningless and nothing but a hollow sentimental expression? Is not human dignity nothing more than a conveniently contrived notion without basis in reality? And if we are nothing but highly organized inanimate particles, what is the basis for claims to ‘human rights’? These basic questions know no geographic boundaries and are asked by thinking people everywhere
Kita (manusia) ini bernilai, lalu apa dunia ini juga demikian?
Misal nih, kamu dimasukkan ke dalam suatu ruangan sama semua hal yang kamu suka: games, makanan, minuman, orang-orang tercinta, tapi di saat yang bersamaan kamu juga tau bahwa dunia ini akan hancur dalam lima menit, seberapa berharga kah semua yang kamu miliki itu? Nothing 🙃. Sama seperti umur, 75 tahun itu gak berarti apa-apa karena pada akhirnya kita semua mati, dunia ini akan lenyap. Secara fundamental dunia ini tak berharga, tak bernilai sama sekali, semua ini akan dilupakan. Namun dalam Islam, dunia ini tetap bernilai dan berharga karena ia menjadi sarana kita dalam mendekatkan diri kepada Tuhan, berbuat baik, juga menyembah-Nya, yang akan menuntun ke surga abadi.
Tidak Ada Tujuan
Apa maksud dan tujuan kita terlahir di dunia ini? Albert Camus, peraih Nobel Prize, berkata: “Kamu gak akan pernah hidup jika kamu terus mencari arti kehidupan”. Ia pada dasarnya berprinsip untuk hidup dengan kehidupan yang sesuai dengan pribadi masing-masing, tak peduli apa ada kebenaran di luar sana. Tapi on a serious note, masuk akal gak sih kalo kita percaya kita ini punya tujuan?
Untuk membantu menjawab pertanyaan tersebut, coba renungkan: kamu mungkin lagi baca artikel ini sambil duduk di kursi, atau lagi pakai baju. Pertanyaannya: buat apa? Kursi itu buat apa? Ngapain pakai baju? Jawabannya jelas: kursi ya buat duduk, biar nyaman. Pakaian juga sama, menjaga tubuh agar tetap hangat. See, bahkan hal-hal yang kita lihat setiap hari saja punya tujuan (nilai guna). Mereka ini benda mati, gak punya emosi, gak punya kemampuan apa-apa, namun kita tetap menganggap bahwa mereka ini ada gunanya. Lucunya sebagian dari kita masih bilang bahwa keberadaan kita di dunia tak memiliki tujuan sama sekali. Counterintuitive.
Banyak juga yang bilang bahwa ketiadaan ultimate purpose ini justru lebih memberikan kebebasan untuk menentukan tujuan kita sendiri. Ini cacat logika karena mereka pada dasarnya tetap “butuh” tujuan hidup namun di saat yang bersamaan menyangkal keberadaan manusia di dunia ini tanpa tujuan. Sama aja kayak bilang, “Let’s pretend to have purpose”. Juga tak ada bedanya dengan anak-anak yang sedang bermain dokter-dokteran, ibu-ibuan, atau ayah-ayahan. Bagaimanapun, kita harus sadar dan dewasa bahwa hidup ini bukan sekedar main-main.
Mereka yang berpaham Darwinisme mengklaim bahwa tujuan manusia hidup ini hanya untuk meneruskan DNA; seperti yang Richard Dawkins kemukakan di dalam bukunya The Selfish Gene, dimana tubuh kita sudah mengembangkan kemampuan untuk melakukan hal itu semata. Masalah dengan pandangan ini adalah ia merendahkan derajat manusia sebagai produk “gak sengaja” (bahasa kasarnya: kondom bocor 😄) dari proses alam semesta yang acak, buta, dan non-rasional. Manusia dianggap sebagai entitas yang tiba-tiba terbentuk dari bubur molekul yang diaduk-aduk (sama kerupuknya juga ya). Lalu tiba-tiba kita manusia punya tujuan. What?
Tidak Ada Kebahagiaan yang Kekal dan Berarti
Semua ingin bahagia. Gak usah ditanya lagi. Tapi kenapa kita ingin bahagia? 🤔 Gak ada yang tahu, karena kebahagiaan itu adalah tujuan akhir, bukan perjalanan. Gak heran kita tanpa henti mencari berbagai cara untuk merasa bahagia. Lalu muncul pertanyaan: Apa sih kebahagiaan sejati itu?
Coba bayangin: Selagi baca artikel ini, kamu dibuat tak sadarkan diri entah oleh siapa. Bangun-bangun kamu ada di pesawat mewah, makanannya enak, pramugarinya cantik-cantik, segala macam entertainment ada di situ, first class pokoknya. Lalu tak terasa waktu berlalu, dan kamu mulai bertanya pada diri sendiri: Would I be happy?
Ya gimana bisa, kamu harus cari tahu dulu jawaban dari beberapa pertanyaan berikut: Siapa yang menculik kamu? Gimana kamu bisa ada di pesawat? Maksud dari perjalanan ini apa? Kemana kamu pergi? Jika pertanyaan-pertanyaan ini belum bisa dijawab, gimana bisa bahagia?
Sekarang aplikasikan renungan tadi ke kehidupan kita: apa kita sudah bahagia? Munculnya kita ke dunia ini hampir tak ada bedanya dengan kita yang disekap dan muncul tiba-tiba di dalam pesawat. Kita tak pernah memilih kapan tanggal lahir kita, siapa orangtua kita, atau darimana kita berasal. Sayangnya banyak dari kita tidak pernah menanyakan persoalan ini atau mencoba mencari jawabannya untuk mendapatkan kebahagiaan sejati.
Lalu apa itu kebahagiaan sejati? Jika kita menilik pembahasan barusan, kebahagiaan sejati itu ada di balik jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, termasuk: Apa tujuan kita hidup? Kemana kita akan pergi setelah mati? Jika ada sebagian dari kita yang mengaku sudah mendapatkan kebahagiaan sejati namun belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas, maka kebahagiaannya tak begitu berarti. Sama seperti orang mabuk yang terlihat bahagia padahal ia hanya sedang lupa dengan realita kehidupan. Sama seperti orang yang mengaku bahagia di pesawat mewah tadi tanpa tahu siapa yang menculiknya dan kemana ia akan pergi.
Di bawah paham naturalisme, persoalan tadi tak benar-benar memiliki jawaban. Kenapa kita ada di sini? Gak ada alasannya sama sekali. Kemana kita pergi? Gak kemana-mana. Kita hanya menunggu kematian saja.
Dalam Islam, jawabannya sangat sederhana: kita di sini untuk menyembah Tuhan (dibahas di Bab 15).
Namun “menyembah” (ibadah) dalam Islam itu agak berbeda dari pemahaman kata tersebut pada umumnya. Bentuk sembahan dalam Islam bisa ditemui di aktifitas sehari-hari: senyum, membersihkan rumah, berkata jujur, merawat diri, beristrirahat, dan lain sebagainya. Mencoba mengenal Tuhan pun termasuk menyembah. Selama kita fokuskan apa yang kita lakukan untuk-Nya, maka bisa dibilang kita sedang menyembah-Nya.
Jika kita tak menyembah-Nya, maka kita akan menyambah tuhan-tuhan yang lain. Pasangan kita, bos kita, teman-teman kita, lingkungan kita, bahkan keinginan kita sendiri ‘memperbudak’ kita dengan cara tertentu. Yang gampang nih, coba tanyain kenapa kita suka pakai baju bagus? Pasti kebanyakan jawabnya: biar keliatan bagus. Kita ingin orang lain melihat kita bersih, rapih, dan civilized. Dalam hal ini, orang-orang sekitar kita itu adalah ‘majikan’ kita.
Dalam Islam, Allah adalah satu-satunya ‘majikan’. Jika kita mengharapkan kepuasan dari sesuatu yang limited, seperti dunia ini, secara logis, apa yang kita dapatkan pun akan limited. Tuhan itu unlimited, dan Ia mampu memberikan sesuatu melebihi ekspektasi kita.
Di sini saya pribadi sempat bertanya-tanya dan berdiskusi dengan istri: apa betul hanya dengan menyembah-Nya saja bisa memberikan kebahagiaan sejati? Dimana korelasinya? Saya mengerti dan paham analogi pesawat di atas. Namun bagaimana dengan mereka yang disekap lalu bangun di dalam kabin pesawat economy class, yang pelayanannya buruk, yang makanan dan minumannya kurang sedap? Sekalipun mereka tahu bagaimana mereka ada di pesawat itu dan kemana akan pergi, apa mereka masih bisa merasa senang (yang betul-betul senang) dengan pelayanan yang buruk itu? Bagaimana seorang yang miskin, yang tak beruntung, yang sengsara bisa merasakan kebahagiaan yang mungkin mudah didapat oleh orang-orang yang lebih beruntung haya dengan menyembah-Nya?
Beberapa jawaban yang saya dapatkan setelah berdiskusi, merenung, dan baca-baca:
-
Happiness is to feel content. Tentram. Untuk orang yang bisa terlepas dari ekspektasi duniawi, ia tak lagi terikat dengan sesuatu yang limited. Ia sekarang terikat dengan Tuhan, entitas yang unlimited. Ia tak lagi peduli dengan apa kata dan opini orang-orang, ia bisa melakukan semua yang ia suka tanpa ‘persetujuan’ orang lain. Karena ia tahu di atas sana ada yang selalu melihat dan peduli.
Jika kamu diberi baju yang paling bagus di dunia ini, apa kamu bakal senang? Bagaimana kalau gak ada orang yang bisa apresiasi baju bagus tadi? What if you didn’t have someone to share your experience with. Apa masih bisa merasa senang?
-
Bagi mereka yang terlihat kurang beruntung namun kenal dengan Tuhannya, ia bisa bersabar atas segala cobaan dan kesusahan di dunia ini. Karena ia tahu di akhirat nanti, semua penderitaan dan jerih payahnya akan dibalas oleh Yang Maha Adil, seperti yang sudah dibahas di atas. Analoginya seperti orang yang mendaki gunung Everest: ia tahu mendaki gunung Everest adalah sesuatu yang berbahaya, banyak harta dan tenaga yang harus dikorbankan, harus bersusah-payah untuk mencapai puncaknya, bahkan banyak orang yang mati di tengah jalan. Lalu kalau sudah tahu itu semua, kenapa masih mau mendaki? Jawabannya jelas, karena ia tahu akan ada kesenangan yang tidak dapat digambarkan ketika mencapai puncak Everest. Ada kepuasan yang sulit diungkapkan ketika berhasil melewati segala kesulitan selama perjalanan.
-
Kalau kita melihat ada rumah bagus dan ingin memasukinya, apa yang kita lakukan? Kita tentu mendekati si pemilik rumah karena ia yang memegang kunci dan lebih tahu isi rumah tersebut. Sama halnya kalau kita ingin mendapat kebahagiaan sejati, seharusnya kita mendekati Ia yang mampu memberi kebahagiaan sejati, Ia yang mampu memberi kecukupan dan ketentraman di hati, Ia yang lebih tahu luar-dalamnya hati manusia.
Dengan alasan-alasan ini, gak heran di dalam al-Qur’an disebutkan:
ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُم بِذِكْرِ ٱللَّهِ ۗ أَلَا بِذِكْرِ ٱللَّهِ تَطْمَئِنُّ ٱلْقُلُوبُ
“(yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenteram.” — QS 13:28
Masuk ke pertanyaan berikutnya: Kemana kita pergi?
Kita punya pilihan: menerima rahmat Tuhan yang tak terbatas, atau lari darinya. Menerimanya —mematuhi perintah-Nya, menyembah-Nya, menjawab panggilan-Nya— akan menuntun kita ke surga. Menolaknya, maka kita akan berakhir di tempat tanpa kasih-Nya, neraka. Kita memiliki free will untuk memilih. Meskipun Tuhan ingin yang baik-baik untuk kita, tapi Ia tak akan memaksa kita untuk membuat pilihan yang benar. Kita diberi akal dan kebebasan untuk menentukannya sendiri.
Kesimpulan
Singkatnya, ateisme tidak dapat memberikan jawaban mendalam soal keberadaan kita. Oleh karenanya, konsep kebahagiaan sejati tinggal angin lewat saja. Jika ada yang mengaku-ngaku sudah bahagia, maka kebahagiaannya semu, seperti orang mabuk yang terlihat bahagia. Di bawah naturalisme, segalanya tak berarti apapun.
Bahkan Richard Dawkins pun mengaminkan,
On the contrary, if the universe were just electrons and selfish genes, meaningless tragedies like the crashing of this bus are exactly what we should expect, along with equally meaningless good fortune. Such a universe would be neither evil nor good in intention. It would manifest no intentions of any kind. In a universe of blind physical forces and genetic replication, some people are going to get hurt, other people are going to get lucky, and you won’t find any rhyme or reason in it, nor any justice. The universe we observe has precisely the properties we should expect if there is, at bottom, no design, no purpose, no evil and no good, nothing but blind, pitiless indifference.
Alam semesta yang terbentuk dari materi fisik yang non-rasional, buta, dan dingin semestinya tak punya kaitan apapun dengan emosi kita. Kita hanya kumpulan molekul dan atom. Hanya Tuhan yang mampu menyediakan justifikasi intelektual terhadap apa-apa yang membentuk kemanusiaan kita.
… [Bersambung ke Bab 3]